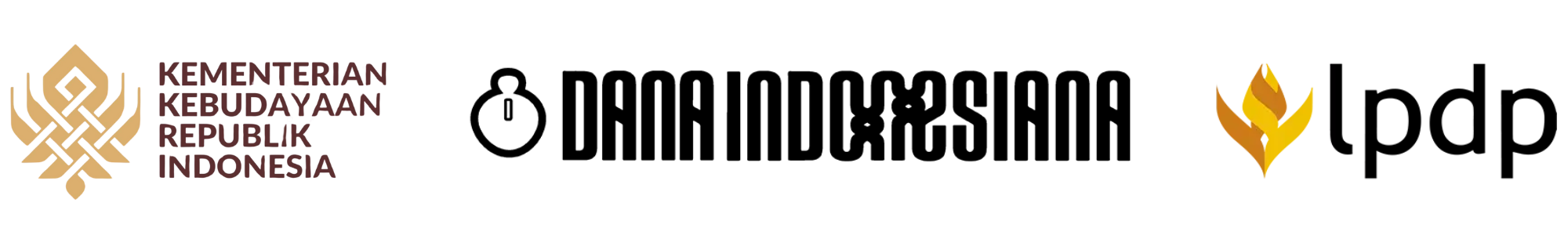Seperti halnya roda yang terus berputar, hidup kadang berada di atas, kadang di bawah. Begitu pula dengan perjalanan usaha batik Oey Soe Tjoen. Setelah berhasil merangkak naik hingga mendapat perhatian dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer tahun 1938, batik Oey Soe Tjoen mulai goyah saat penjajahan Jepang datang pada tahun 1942. Krisis yang datang bersama kedatangan Jepang menjadi salah satu tantangan terberat yang dihadapi Oey Soe Tjoen sepanjang merintis usahanya.
Saat Jepang menduduki Indonesia, situasi politik dan ekonomi menjadi sangat tidak menentu. Kehidupan masyarakat di berbagai lapisan semakin sulit. Bertahan hidup dalam kondisi yang serba terbatas bukanlah hal yang mudah, termasuk bagi pengusaha batik di Pekalongan. Di tengah ketidakpastian tersebut, Oey Soe Tjoen berjuang keras untuk mempertahankan usaha batiknya.
Pada saat Jepang tiba, kekacauan terjadi di mana-mana. Jepang, yang berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, pada akhir 1941, berusaha merebut negara-negara di Asia Timur dan Tenggara dari kekuasaan Barat, termasuk HIndia Belanda, yang sebelumnya dikuasai Belanda. Jepang akhirnya menginvasi Hindia Belanda dan mengusir kolonial Belanda. Selama masa transisi kekuasaan itu, ketegangan dan ketidakpastian semakin tinggi, terlebih bagi kelompok peranakan Tionghoa.
Kwee Netti, istri Oey Soe Tjoen, selalu menceritakan kisah pahit dan krisis yang mereka alami saat peralihan kekuasaan ini kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Rumah batik Oey Soe Tjoen berada di ujung tanduk saat masa-masa itu. Pada tahun 1942, rumah mereka di Kedungwuni menjadi salah satu sasaran penjarahan besar yang dipicu oleh berbagai faktor: kesulitan hidup yang melanda masyarakat, serta tuduhan tanpa dasar bahwa warga Tionghoa adalah antek-antek Belanda. Jepang, yang saat itu dianggap sebagai penyelamat, membuat masyarakat pribumi sangat sensitif terhadap segala hal yang berbau kolonial Belanda.

Penjarahan ini merupakan pukulan berat bagi Oey Soe Tjoen dan keluarganya. Pada saat itu, pasukan Belanda yang biasa menjaga pos-pos keamanan telah meninggalkan daerah tersebut, sementara serdadu Jepang yang seharusnya menjaga keamanan belum juga datang. Hal ini dimanfaatkan oleh massa yang datang dari luar Kedungwuni untuk melakukan penjarahan. Oey Soe Tjoen sangat menyadari bahwa penjarah itu bukan berasal dari Kedungwuni, karena ia tidak mengenal satu pun wajah mereka.
Penjarahan datang tiba-tiba. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah penjarahnya, namun Oey Soe Tjoen dan karyawannya yang saat itu sedang bekerja membatik terpaksa melarikan diri melalui pintu belakang. Mereka berlari dan bersembunyi di rumah yang dianggap aman. Setelah beberapa waktu, saat kembali ke rumah Kidul, mereka menemukan rumah dalam kondisi kosong melompong. Semua barang dan perabotan hilang, termasuk kain batik yang sudah selesai maupun yang belum selesai. Bahkan piagam dan penghargaan dari Gubernur Jenderal Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer pun ikut digondol para penjarah.
Semua harta Oey Soe Tjoen ludes, hanya menyisakan pakaian yang dikenakannya dan beberapa pakaian kotor yang sedang direndam di ember. Hingga kini, pakaian-pakaian tersebut masih tersimpan dalam koleksi batik keluarga Oey Soe Tjoen. Masa itu merupakan masa terberat bagi Oey Soe Tjoen, karena harus memulai lagi usaha batiknya dari nol, akibat hampir semua hartanya telah habis dijarah.
Meski usaha batik Oey Soe Tjoen mulai pulih, krisis belum sepenuhnya berlalu. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ketegangan masih terus terjadi. Pada tahun 1947, tepat dua tahun setelah kemerdekaan, Kedungwuni kembali dilanda huru-hara besar, bertepatan dengan agresi militer Belanda pertama yang berusaha merebut kembali Indonesia.
Pengalaman pahit dari penjarahan pertama membuat Oey Soe Tjoen dan Kwee Netti lebih waspada. Mereka tahu bahwa ketidakpastian politik, ekonomi, dan keamanan akan membuka kemungkinan penjarahan kembali. Terlebih, komunitas Tionghoa seringkali menjadi sasaran saat terjadi kerusuhan. Oleh karena itu, mereka menyembunyikan harta benda penting dan beberapa kain batik ke dalam ember, lalu menguburnya di halaman belakang rumah.

Upaya ini terbukti berhasil. Harta benda mereka dapat diselamatkan. Namun nyawa mereka hampir saja melayang. Saat penjarahan kedua terjadi pada tahun 1947, para penjarah memisahkan perempuan dan anak-anak dari laki-laki. Para perempuan dan anak-anak dikumpulkan di rumah besar milik warga Tionghoa, Hoo Tjien Siong, dan diawasi ketat seperti tawanan. Sementara itu, Oey Soe Tjoen bersama para pria Tionghoa lainnya digiring keluar desa untuk dieksekusi. Dalam keadaan tersebut, Oey Soe Tjoen dan beberapa pria lainnya berhasil melarikan diri dan selamat kembali ke desa, bertemu lagi dengan keluarga mereka.
Kedua peristiwa penjarahan yang dialami Oey Soe Tjoen dan komunitas Tionghoa lainnya di Kedungwuni pada 1942 dan 1947 menjadi bagian dari sejarah kelam Indonesia pada masa “bersiap”. Periode itu ditandai dengan banyaknya korban, tidak hanya dari golongan Belanda dan Indo-Eropa, tetapi juga dari komunitas Tionghoa. Pelaku penjarahan adalah kelompok-kelompok yang berjuang di bawah bendera perjuangan kemerdekaan, termasuk nasionalis muda dan gerombolan kriminal.
Selama masa revolusi, golongan Belanda, Indo-Eropa, dan Tionghoa sering kali menjadi sasaran karena sentimen rasial. Diperkirakan, korban etnis Tionghoa mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu, selama masa bersiap. Untuk melindungi diri, komunitas Tionghoa kemudian membentuk Pau An Tui, sebuah pasukan yang bertugas menjaga keselamatan mereka dari kekerasan, pencurian, dan penjarahan.
Oey Soe Tjoen dan keluarganya termasuk yang beruntung. Meskipun dua kali menjadi korban penjarahan, mereka selamat dan berhasil melanjutkan usaha batiknya. Namun, meskipun keadaan mulai tenang, usaha batik Oey Soe Tjoen tidak lepas dari tantangan. Setiap kali terjadi peralihan kekuasaan atau dinamika politik di Indonesia, komunitas Tionghoa sering menjadi korban. Salah satunya adalah pasca peristiwa politik 1965, ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan orang Tionghoa mengganti nama mereka dengan nama Indonesia. Akibatnya, Oey Soe Tjoen harus mengganti namanya menjadi Soetjondro Widjaja, dan toko batiknya yang semula bernama “Batik Oey Soe Tjoen” berubah menjadi “Batik Art”. Meskipun demikian, Oey Soe Tjoen tetap membubuhkan tanda tangannya di kain batik yang dijual dengan nama asli.
Begitulah perjalanan Oey Soe Tjoen dalam merintis usaha batik di tengah masa-masa penuh gejolak. Tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga ancaman yang hampir merenggut nyawanya. Namun karena daya tahan dan semangat pantang menyerah Oey Soe Tjoen dan Kwee Netti, menjadikan warisan batik Oey Soe Tjoen begitu berharga. Lebih dari sekadar karya seni yang indah, batik ini adalah simbol perjuangan, ketekunan, dan tekad yang tak pernah pudar untuk terus berkarya.