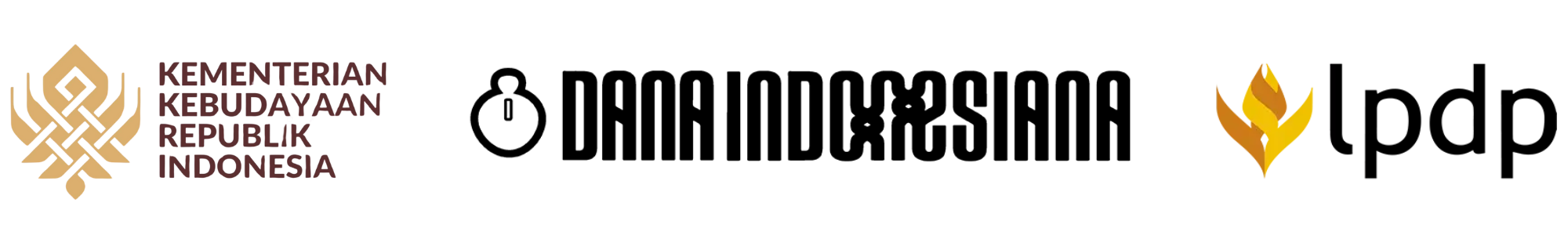Motif buketan merupakan salah satu karya Oey Soe Tjoen yang paling melegenda. Sejak usaha batiknya dirintis pada 1925 dan bertahan hingga satu abad kemudian di tangan generasi ketiga, motif ini selalu menjadi produk unggulan. Menariknya, tidak banyak yang mengetahui bahwa buketan sejatinya bukan bagian dari tradisi batik Jawa. Motif ini justru dikembangkan oleh para nyonya Indo-Eropa di Hindia Belanda yang memproduksi batik pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Sebagai batik pesisiran, batik Oey Soe Tjoen lahir dari ruang pertemuan berbagai budaya. Lingkungan sosial Pekalongan memungkinkan tradisi Jawa, Tionghoa, Eropa, hingga Jepang melebur dan saling mempengaruhi. Perjumpaan itu melahirkan karya kain batik, melainkan wujud dialog antar budaya, salah satunya melalui motif buketan.

Bahkan ketenaran batik Oey Soe Tjoen hingga saat ini tidak terlepas dari motif buketan yang menjadi unggulan sejak masa awal merintis usaha. Motif itu sendiri terinspirasi dari karya Eliza van Zuylen, pembatik Indo-Eropa yang mempopulerkan rangkaian bunga dalam estetika batik pesisir. Buketan berasal dari kata bouquet, karangan bunga dari Prancis atau Belanda, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk rangkaian bunga dan figur fauna seperti burung, kupu-kupu, merak, atau angsa.
Dalam kesejarahan batik, buketan menjadi ciri khas batik Belanda karena banyak dipengaruhi gaya seni art nouveau yang berkembang di Eropa sekitar tahun 1890–1930. Gerakan itu lekat dengan romantisme Eropa dan kegemaran mengoleksi tumbuhan sebagai simbol keindahan. Tradisi merangkai bunga pada masyarakat Eropa yang tinggal di Hindia Belanda kemudian diterapkan dalam estetika motif batik. Sebagai bentuk pelestarian dan cerminan budaya dari tanah kelahirannya.
Motif buketan juga menandai pergeseran besar dalam tradisi batik pesisir. Sebab dapat menghadirkan sebagai wujud kebebasan dari aturan pakem batik keraton Yogyakarta dan Solo. Di tangan pembatik Indo-Eropa, rangkaian bunga yang bahkan tidak tumbuh di Hindia Belanda, seperti tulip, anggur, hingga krisan Eropa, hadir dalam komposisi yang halus dan rumit, penuh warna meriah. Jauh dari kesan sogan Jawa yang klasik.
Eliza van Zuylen bukan hanya memopulerkan motif buketan, tetapi juga menghadirkan inovasi desain. Dia mengkombinasikan bunga musim semi dan musim gugur, flora Eropa dan Nusantara. Lalu menempatkannya di atas latar polos tanpa motif keraton atau pesisir. Pendekatan itu membedakannya dari pembatik Indo-Eropa lain, sehingga membuat karyanya sangat digemari pasar. Bahkan akibat popularitasnya yang semakin tinggi, orang-orang menyebut batik panselen (pelafalan lokal dari Van Zuylen). Permintaan yang tinggi membuat perusahaannya berkembang pesat hingga menjadi pabrik batiknya di Pekalongan menjadi yang terbesar di Hindia Belanda pada tahun 1918 silam. Kegemilangan panselen itu kemudian menginspirasi banyak pengusaha batik, termasuk para peranakan Tionghoa.

Pengusaha batik peranakan Tionghoa awalnya memadukan gaya Eropa dan Cina dalam karya mereka. Namun pengaruh batik Indo-Eropa yang kian kuat membuat mereka mengadopsi motif buketan sebagai komoditas unggulan. Mereka memasukkan unsur budaya Tionghoa, seperti filosofi Taois dan Konfusian. Serta meniru detail ukiran kayu, porselen, dan sulaman Cina. Flora Cina seperti lotus, teratai, dan krisan dikombinasikan dengan bunga-bunga Eropa.
Ciri khas khas peranakan Tionghoa terlihat pada isen-isen berupa cocohan, yakni titik-titik kecil menyerupai butiran padi yang memenuhi latar kain. Mereka umumnya memproduksi kain sarung atau kain panjang dengan pembagian motif yang sistematis dalam membuat buketan. Yakni satu buketan bunga di kepala kain, dan tiga hingga empat buketan bungan pada bagian badan.
Situasi politik turut mendukung perkembangan motif buketan. Peraturan gelijkgesteld (1910) memberi status kelas kedua kepada keturunan Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda, setingkat di bawah orang Eropa. Hal itu memberi rasa percaya diri untuk meniru dan kemudian mengembangkan motif Indo-Eropa, sehingga melahirkan gaya hibrid, buketan Eropa dalam bingkai estetika Cina.
Dari seluruh pengusaha peranakan Tionghoa, nama Oey Soe Tjoen muncul sebagai salah satu pembatik yang memiliki karya buketan yang indah dan halus. Salah satu keistimewaan karyanya terletak pada isen-isen berupa titik-titik kecil yang sangat halus, membentuk garis-garis putus. Motif itu menjadi pembeda yang menonjol yang kemudian juga ditiru pula oleh Eliza van Zuylen. Kehalusan batik Oey Soe Tjoen begitu terkenal hingga muncul anggapan bahwa ia menggunakan canting emas. Walaupun anggapan itu dibantah oleh pihak keluarga. Oey Kiem Lian, cucu Oey Soe Tjoen mengungkapkan bahwa canting yang digunakan sama seperti pembatik lain. Menurutnya istilah the golden canting muncul dari wartawan asing yang memuji tingkat keterampilan, kesabaran, dan presisi para pecantingnya. Sang wartawan menyebut the golden canting terhadap pecanting yang menghasilkan batik yang sangat halus dengan pencantingan yang sangat bagus dan indah. Penerimaan secara harfiah akhirnya membuat orang beranggapan canting yang digunakan Oey Soe Tjoen terbuat dari emas.
Selain terkenal halus, salah satu keunggulan lain dari batik Oey Soe Tjoen terletak pada teknik pewarnaan. Sebab dia mampu menghadirkan tiga hingga empat warna dalam satu kain, pada kedua sisinya, dengan gradasi yang sangat halus. Proses itu tentu membutuhkan pengulangan pencantingan, pencelupan, dan nglorod berkali-kali. Ketekunan dan keteguhan hati sangat diperlukan dalam setiap prosesnya, karena dengan proses pewarnaan yang berulang kali membutuhkan waktu yang lama.
Berbeda dari Eliza van Zuylen yang menggemari warna pastel, Oey Soe Tjoen memilih warna-warna cerah seperti kuning, ungu, hijau, dan merah jambu, sesuai selera pelanggan peranakan Tionghoa. Figur-figur bermakna dalam budaya Cina seperti burung bangau, naga, bunga seruni, mewarnai karya-karyanya sebagai simbol keberuntungan.