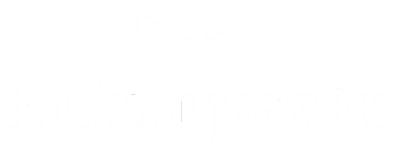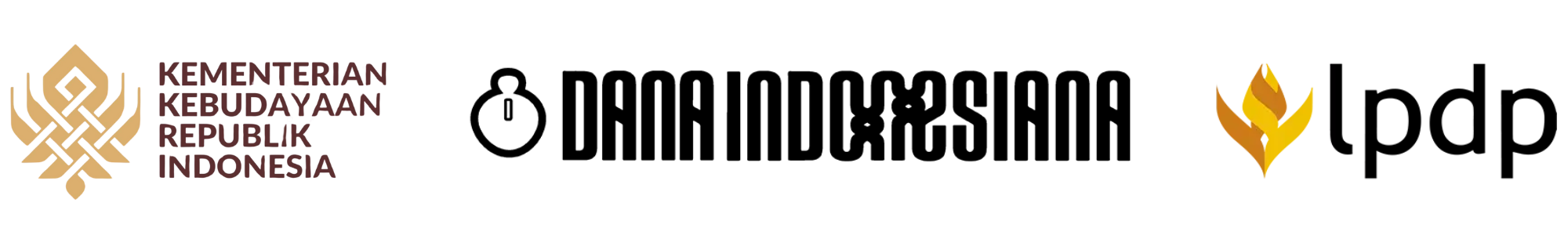Pernah mendengar tentang Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)? Gabungan koperasi-koperasi batik ini berdiri pada 1948. Tepatnya pada tanggal 18 September, bertempat di Kantor Kementerian Kemakmuran, Jalan Malioboro nomor 85, Yogyakarta.[1] GKBI didirikan dengan tujuan menjadi wadah untuk mengorganisasi koperasi-koperasi batik di seluruh Indonesia kala itu.
GKBI sebenarnya merupakan perkembangan dari Persatuan Pengusaha Batik Indonesia (PPBI) yang sebelumnya bernama Persatuan Perusahaan Batik Bumi Putera (PPBBP). PPBBP berdiri pada tahun 1939 ketika dunia baru saja mentas dari “depresi ekonomi” yang terjadi sekitar tahun 1930. Singkatnya, PPBBP muncul dengan harapan menjadi jawaban atas bayang-bayang kebangkrutan industri dan perdagangan batik Indonesia pascakrisis global.
Tapi artikel ini tidak berbicara mengenai perjalanan lahirnya GKBI, melainkan akan menunjukkan salah satu aksi penting yang pernah organisasi ini lakukan. Ya, GKBI pernah mengeluarkan resolusi pada tahun 1953, lima tahun setelah organisasi ini lahir. Resolusi tersebut mereka beri nama “Resolusi Koperasi Batik” yang dirumuskan dalam konferensi GKBI tahun 1953 di Jakarta.
Konferensi yang akhirnya menelurkan resolusi tersebut boleh dibilang merupakan suatu tindakan politik monumental dalam perjalanan sejarah GKBI. Sebab resolusi tersebut mampu membuat pemerintah–dalam hal ini Menteri Perekonomian kala itu yakni Iskaq Tjokrohadisurjo–membatalkan salah satu kebijakan ekonomi yang GKBI nilai akan melumpuhkan koperasi-koperasi batik.
Program Benteng dan Hak Tunggal Impor
Pada tahun 1950, Pemerintah Indonesia mencanangkan kebijakan ekonomi bernama Gerakan Benteng atau Program Benteng. Program ini merupakan ide dari Menteri Perdagangan kala itu yakni Soemitro Djojohadikusumo dalam Kabinet Natsir. Program ini dicanangkan sebagai upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi yang semula masih cenderung mengakomodasi kepentingan pengusaha asing hendak diubah agar lebih berpihak kepada pengusaha domestik. Salah satu gerakan program ini ialah membatasi impor barang-barang tertentu, namun juga seraya memberi lisensi (izin) impor kepada pihak tertentu.[2]
Dalam skema ekonomi tersebut, GKBI mendapat posisi istimewa. Mereka memeroleh hak tunggal impor dan distribusi kain mori (cambrics) yang merupakan bahan baku batik. Pemerintah memberi hak ini sebagai proteksi terhadap industri batik nasional yang memang banyak membutuhkan bahan baku. GKBI akhirnya melenggang menjadi agen pelaksana impor kain mori untuk kemudian didistribusikan kepada anggotanya (koperasi-koperasi batik).
GKBI Terusik
Belum jenak GKBI berada di posisi nyaman sejak mendapat hak tunggal impor, angin berembus mengganggu ketenangan mereka. Angin tersebut datang seiring dengan pergantian kabinet pemerintahan, dari Kabinet Wilopo (Masyumi) ke Kabinet Ali Sastroamidjojo I (PNI). Angin berembus makin kencang hingga mengusik GKBI kala Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo–yang juga dari PNI (Partai Nasional Indonesia)–mengeluarkan kebijakan yang hendak mencabut hak tunggal impor kain mori dari GKBI dan dialihkan ke perusahaan lain, yakni NV Suez dan NV Goenoeng Perahoe.[3] Kebijakan ini mulai berlaku pada 9 September 1953.[4]

Penulis belum menemukan data bagaimana respons atau reaksi awal GKBI atas kebijakan pencabutan hak tunggal impor sebelum mereka mendengungkan Resolusi Koperasi Batik. Apabila memang tak ada, artinya Resolusi Koperasi Batik merupakan reaksi paling awal dan resmi dari GKBI atas kebijakan tersebut. Bukan tidak mungkin ada reaksi-reaksi kecil yang sifatnya tak resmi, namun sepertinya Resolusi Koperasi Batik adalah satu-satunya reaksi paling jelas dan politis dari GKBI.
Isi Resolusi Koperasi Batik Indonesia
Resolusi Koperasi Batik dirumuskan GKBI melalui konferensi yang mereka gelar di Jakarta pada 20-22 September 1953, hanya berselang 11 hari setelah hak impor mereka dicabut Menteri Iskaq. Ini agaknya menunjukan betapa GKBI benar-benar memandang penting hak impor tersebut. Mereka dengan segera menggelar konferensi dan mengeluarkan resolusi.
Penulis menemukan resolusi tersebut dimuat di surat kabar salah satunya De Nieuwsgier edisi 23 September 1953.[5] Resolusi Koperasi Batik dimuat di surat kabar tersebut dengan ukuran setengah halaman dan berbentuk seperti iklan (bukan berbentuk teks/format kolom berita). Resolusi Koperasi Batik dibuka dengan kalimat-kalimat bernada seruan dan langsung menunjuk hidung Menteri Iskaq: “Hentikan Tindakan Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo Menteri Perekonomian menyerahkan impor cambrics (kain mori) kepada importir-importir tertentu”. Kemudian dilanjut dengan kalimat “Serahkan kembali kepada Gabungan Koperasi Batik Indonesia” lalu “Tindakannya melumpuhkan koperasi dan bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.”
Masuk ke bagian berikutnya, GKBI mengutarakan bahwa Resolusi Koperasi Batik mereka keluarkan dari hasil Konferensi Batik yang dihadiri 85 orang perwakilan dari 20 koperasi batik yang beranggotakan 7.000 pengusaha batik. Selanjutnya GKBI menyampaikan tujuh poin pendapat terkait kebijakan hak impor kain mori yang beberapa tahun terakhir mereka pegang.
Tujuh poin pendapat tersebut intinya sebagai berikut: Pertama, GKBI menilai kebijakan pemerintah memberikan hak impor kain mori kepada mereka merupakan langkah tepat karena untuk melindungi produksi batik Indonesia dan sesuai cita-cita gerakan koperasi; Kedua, GKBI merasa pemberian hak impor kain mori kepada mereka dapat menjamin kuatnya posisi permintaan (batik) Indonesia di pasar luar negeri dalam segi harga dan kualitas; Ketiga, distribusi bahan-bahan batik melalui GKBI dapat menjamin tercapainya produksi batik sesuai pasar, menstabilkan harga cambrics dan grey, serta menjamin kontinuitas stok bahan baku batik agar terhindar dari spekulasi perdagangan; Keempat, GKBI menilai langkah pemusatan penjualan eceran ke tangan pengusaha batik yang berada di lingkaran koperasi–seperti yang sudah berjalan–dapat melepaskan pengusaha kecil dari genggaman pengusaha besar sekaligus menekan praktik riba; Kelima, GKBI mengklaim hak impor kain mori yang mereka jalankan membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat karena bahan baku lebih murah; Keenam, GKBI mengklaim para anggotanya telah merasakan banyak manfaat dari hak impor hingga bisa menggunakan sebagian keuntungan mereka untuk keluarga besar GKBI (bantuan sosial untuk pembatik dan pekerja batik) serta masyarakat; Ketujuh, GKBI mengklaim impor kain mori mereka tak sampai 5 persen dari total jumlah impor Indonesia.
Berangkat dari tujuh pendapat tersebut, GKBI memandang kebijakan Menteri Iskaq mencabut hak impor kain mori dari mereka merupakan bentuk menghalang-halangi kemajuan dan perkembangan koperasi batik sekaligus bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar. Maka dalam Resolusi Koperasi Batik itu GKBI memutuskan tiga poin, yakni: 1) Mendesak pemerintah membatalkan kebijakan Menteri Iskaq dan mengembalikan hak impor kain mori kepada GKBI, 2) GKBI akan mengutus delegasi untuk menyampaikan resolusi ini kepada Menteri Iskaq, 3) Menyampaikan pula resolusi ini kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Gerakan Koperasi Indonesia Bung Hatta, Dewan Koperasi Indonesia, Pusat Jawatan Koperasi di Kementerian Perekonomian, serta kepada pers dan umum.
Dua puluh koperasi batik yang hadir di konferensi GKBI yakni KPB Djakarta, Mitra Batik Tasikmalaja, CPBB Tjiamis, Trusmi Tjirebon, Perbain Purwokerto, Gaperbi Tegal, Setono Pekalongan, PPIP Pekalongan, Wonopringgo Pekalongan, Pekadjangan Pekalongan, Perbaik Purworedjo, Sakti Kebumen, PPBI Jogjakarta, Batari Surakarta, Kobain Kudus, Perbis Semarang, Bakti Ponorogo, KPB Gresik, BTA Tulungagung, KBI Sidoardjo.
Menteri Iskaq Mencabut Kebijakannya
Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo akhirnya mencabut kebijakannya, hak impor kain mori kembali ke tangan GKBI. Selain karena protes dari GKBI lewat Resolusi Koperasi Batik, penentangan di parlemen turut menjadi faktor yang mendesak Iskaq mencabut kebijakannya. Termasuk pula tekanan-tekanan publik karena keberadaan GKBI kala itu dipandang banyak kalangan harus dipertahankan dalam skema ekonomi nasional dan Program Benteng karena menyangkut ribuan pengusaha batik bumi putra yang meski dengan segala keterbatasan namun menunjukkan kemampuan berkembang.[6]
Sejak didirikan pada 1948, dalam jangka waktu setahun GKBI sudah bisa mendirikan anak perusahaan bernama NV Batik Trading Company (BTC) yang didesain untuk menjadi agen impor kain mori dan bahan-bahan pembatikan lainnya. Walaupun pada 1953, ketika GKBI mendapat pengesahan badan hukum, mereka melikuidasi (membubarkan) anak perusahaan tersebut dan mengambil alih semua pekerjaan-pekerjaan impor.[7] Pada 1953 pula GKBI sudah mampu membeli gedung sendiri sebagai kantor mereka, di Jalan Pinangsa, Jakarta. Sebelumnya, pada 1952, GKBI hanya menumpang di Kantor Djohan-Djohor, Kalibesar Barat, Jakarta.[8] Di luar itu, industri batik terbukti mampu melewati masa krisis 1930.
Usai bersitegang dengan Menteri Iskaq, GKBI pun tak menyia-nyiakan kepercayaan dalam memegang kembali hak impor kain mori. Bahkan sampai Program Benteng dihentikan pada 1957, GKBI tetap memegang hak tersebut.[9] Selepas itu GKBI masih terus berjalan dengan capaian-capaiannya antara lain mendirikan Pabrik Cambrics Medari Jogjakarta pada 1957 dengan anggaran Rp120 juta, pada 1958 (lima tahun setelah resolusi) jumlah simpanan dan cadangan mereka mencapai Rp418,4 juta, jumlah distribusi mori 62 juta yard, omzet Rp935,2 juta, dan modal kerja Rp437,6 juta. Omzet mereka selalu naik sejak tahun 1954 sebesar Rp416,7 juta, menjadi Rp935,2 juta pada tahun 1958, kecuali pada tahun 1956 ke 1957 yang tetap di angka Rp702,9 juta.[10]
Penutup
Resolusi Koperasi Batik boleh dibilang menjadi salah satu portofolio perjuangan sekaligus keberhasilan GKBI dalam melindungi anggota mereka (koperasi-koperasi batik) dari kemungkinan kebangkrutan. Menurut penulis, peristiwa berhadap-hadapannya GKBI dengan pemerintah tahun 1953 itu layak menjadi catatan penting dalam sejarah industri batik di Indonesia. Kondisi industri batik mungkin akan berada di lain cerita apabila GKBI kala itu tak ambil sikap menentang atau seandainya resolusi mereka tak dihiraukan pemerintah.
[1] Chiyo Inui Kawamura, “Peralihan Usaha dan Perubahan Sosial di Prawiratman, Yogyakarta 1950-1900-an”, Tesis: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2004. Dikutip pula oleh Khotifah, “Perubahan Sosial dan Ekonomi Kampung Prawiratman Yogyakarta 1920-1975”, Skripsi: Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. 2013. hlm. 62. Ketika Ibu Kota Republik Indonesia kembali ke Jakarta, kantor pusat GKBI ikut dipindahkan ke Jakarta.
[2] Reny Y. Sinaga, “An Interpretative and Critical Paradigm Study of the ‘Gerakan Ekonomi Benteng’ in Indonesia”, The Scientia Journal of Economics Issues, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 2.
[3] NV adalah singkatan dari Naamloze Vennootschap (bahasa Belanda). Terjemahannya dalam bahasa Indonesia: Perseroan Terbatas (PT). NV Suez dan NV Goenoeng Perahoe punya hubungan diam-diam dengan Iskaq dan PNI, baca artikel Hendri F. Isnaeni, Menteri Lisensi Tersangkut Korupsi, https://www.historia.id/article/menteri-lisensi-tersangkut-korupsi (harus berlangganan/premium).
[4] Pengurus GKBI, 20 Tahun GKBI: 1948-18 September – 1968, (Koperasi Pusat GKBI dan CV Kosen, 1969), hlm. 36
[5] De Niuewsgier, 23 September 1953
[6] Amin Mudzakir, Perkembangan Ekonomi Pengusaha Santri di Tasikmalaya 1930-1980-an, https://lafadl.wordpress.com/2006/12/25/perkembangan-ekonomi-pengusaha-santri-di-tasikmalaya1930-1980-an/?utm_source=chatgpt.com (diakses pada 27 Juni 2025)
[7] Pengurus GKBI, op. cit., hlm. 36
[8] Ibid., hlm. 36
[9] Amin Mudzakir, op. cit.
[10] Pengurus GKBI, op. cit., hlm. 48-59.