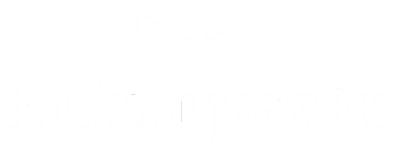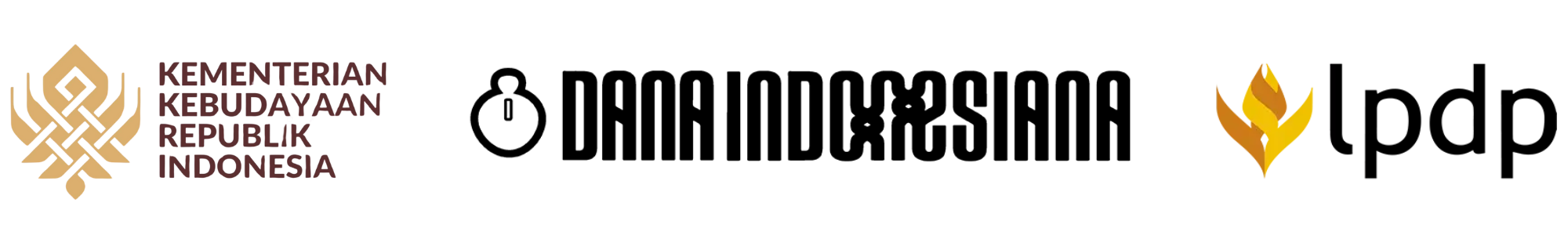“Kota batik di Pekalongan, bukan Jogja, bukan Solo”
Penggalan lagu dari Slank berjudul “Sosial Betawi Yoi” itu mungkin terdengar mengejutkan bagi sebagian orang. Bukankah selama ini Yogyakarta dan Solo dianggap sebagai dua kota utama dalam peta batik Indonesia? Tapi jika kita menelusuri jejak sejarah, ada kebenaran yang tak bisa disangkal: bahwa Pekalongan adalah jantung industri batik yang berdetak sejak abad ke-19, bahkan mungkin lebih awal.
Pekalongan Kota Industri Batik
Tak sulit memahami mengapa Pekalongan dijuluki Kota Batik. Di masa kolonial Belanda, kota pesisir utara Jawa ini telah menjadi episentrum produksi dan perdagangan batik. Dalam laporan tentang hasil survei mengenai kondisi kerja di pabrik-pabrik batik di Jawa dan Madura oleh P de Angelino pada tahun 1930, disebutkan bahwa batik Pekalongan bukan hanya diperdagangkan secara lokal, melainkan juga komoditas ekspor yang dikirim melalui jalur laut, pos, dan kereta api ke berbagai penjuru Hindia Belanda. Bahkan hingga Penang, Singapura, dan Suriname.
Bayangkan saja, dalam catatan itu, pada tahun 1925 saja, nilai ekspor batik dari Pekalongan melalui jalur laut dan pos mencapai ƒ 8.460.907. Jika digabungkan dengan pengiriman tak resmi lewat kereta api dan mobil oleh para makelar, jumlahnya bisa melampaui ƒ 10 juta. Jumlah itu nyaris menyamai total ekspor batik dari Yogyakarta dan Solo (digabung). Pada tahun tersebut, nilai ekspor kedua kota vorstenlanden itu hanya sekitar f 15 juta.
Penyelamat Ekonomi Rakyat
Batik adalah penyelamat ekonomi bagi warga Pekalongan. Batik bagi warga Pekalongan bukan hanya kain, melainkan napas kehidupan. Di desa miskin Tegalloeroeng (warga menyebut “Galurung”) misalnya, kehadiran pabrik-pabrik batik menurunkan angka kriminalitas secara signifikan karena membuka lapangan kerja. Bahkan seorang pengawas batik menyebutkan bahwa Pekalongan tanpa pabrik batik bukanlah Pekalongan. Seorang juragan batik yang tidak disebutkan namanya dalam laporan itu juga mengatakan bahwa orang Pekalongan hanya mengenal cangkul dan canting. Tidak heran jika batik menjadi identitas sosial dan budaya bagi orang Pekalongan. Bagi seorang pembatik, membatik adalah laku hidup, bukan sekadar pekerjaan. Sama seperti tanah bengkok bagi petani, batik adalah pegangan hidup.
Tumbuh dan Berkembang Bersama Batik
Lalu sejak kapan sejarah industri batik Pekalongan mulai berkembang? Menilik laporan Mindere Welvaart, Pekalongan sudah aktif dalam perdagangan batik bahkan sebelum tahun 1850. Dari sana, batik diekspor ke Banten yang kala itu sudah tak lagi memproduksi batik. Orang-orang Arab memainkan peran penting sebagai pemasok kain dan modal. Sedangkan perempuan Indo-Eropa menciptakan batik dengan sentuhan artistik tinggi. Lambat laun mulai memperkenalkan motif Eropa, warna-warna baru, serta produk rumah tangga seperti taplak meja dan tirai.
Perkembangan ini mendorong diversifikasi industri batik. Selain perempuan desa yang bekerja untuk juragan Arab atau Tionghoa, muncul pula batikkerijen (pabrik batik) milik wanita-wanita Eropa. Dari sinilah inovasi teknis dan estetika batik berkembang pesat, termasuk penerapan teknik cap yang mempercepat produksi secara massal.
Memang terdapat persaingan selera antara batik vorstenlanden dengan batik pesisir. Alih-alih mengikuti selera aristokrat yang mengagumi warna-warna tenang dan elegan khas batik dari wilayah Vorstenlanden, sebagian besar orang Belanda di Hindia Belanda justru memiliki selera yang berbeda. Mereka, bersama dengan orang Tionghoa dan penduduk non-Jawa lainnya, lebih menyukai kain-kain batik dengan warna mencolok dan motif yang meriah, kain yang umumnya diproduksi di daerah pesisir seperti Pekalongan.

Batik dari daerah pesisir memang dikenal lebih ekspresif dalam hal warna dan corak. Di pusat-pusat produksi batik seperti Pekalongan, batik dengan warna merah cerah, biru muda, hijau, dan berbagai kombinasi warna mencolok lainnya yang justru laris manis di pasaran. Pada 1880, sebuah sensus mencatat ada sekitar 5.000 pembatik di Pekalongan, belum termasuk mereka yang terlibat dalam proses pewarnaan, penyabunan, pengerjaan kain prada, hingga jaringan bakul dan pedagang.
Batik dalam Arus Global
Dengan dibangunnya jalur trem (kereta api) di pesisir utara Jawa, distribusi batik semakin luas. Pasar Malam Pekalongan yang rutin digelar menjadi ajang promosi efektif. Pembeli dari luar daerah berdatangan, melihat langsung proses dan kualitas batik, lalu kembali sebagai pelanggan tetap.
Batik Pekalongan pun melintasi samudra: dikirim ke Sumatra, Kalimantan, Jambi, Eropa, Amerika, bahkan Hindia Barat. Di pasar internasional, batik murah dari blacu Jepang diekspor untuk buruh perkebunan, sementara batik kelas atas dengan bahan dan pewarna berkualitas tinggi menyasar pasar menengah ke atas. Pedagang Arab dikenal sebagai eksportir batik murah, sementara Tionghoa lebih banyak memasarkan batik mahal.
Pekalongan: Lebih dari Sekadar Kota Batik
Industri batik Pekalongan pernah dianggap sebagai industri rumah tangga belaka. Namun pada 1925, Residen J.E. Jasper menyebutnya telah berubah menjadi industri produksi massal: sebuah transformasi besar yang membuktikan betapa dinamisnya kota ini dalam merespons perkembangan zaman dan pasar.

Kini, Pekalongan masih menyandang predikat “World’s City of Batik” dari UNESCO. Banyak yang masih berpikir batik adalah milik Solo atau Yogyakarta saja, kota kerajaan yang mendaku batiknya paling adiluhung. Padahal, Pekalongan punya sejarah panjang yang kaya, kompleks, dan berwarna, persis seperti motif batiknya yang khas dan penuh narasi. Jadi, jika suatu saat kamu memakai batik dengan motif flora yang hidup, warna cerah yang memikat, dan garis lembut penuh harmoni, ingatlah satu hal, mungkin, itu bukan dari Solo. Bukan juga dari Jogja. Tapi dari Pekalongan, tempat di mana canting dan sejarah berpadu dalam satu helai kain.